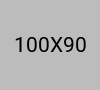JAKARTATERKINI.ID - Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) telah merilis hasil penelitian mengenai bahaya logam timbal dan dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pada anak-anak.
Direktur IMERI-Fakultas Kedokteran (FK) UI, Prof. Dr. Badriul Hegar PhD Sp A(K), menyatakan bahwa penelitian ini didasarkan pada pengalaman warga di lima desa di Indonesia, yaitu Desa Kadu Jaya (Tangerang), Desa Cinangka (Bogor), Desa Cinangneng (Bogor), Desa Pesarean (Tegal), dan Desa Dupak (Surabaya).
Baca juga : Pengamen Pelaku Penusukan Wisatawan di Puncak Bogor Ditangkap Polisi
Riset ini merupakan hasil kolaborasi antara Occupational and Environmental Health Research Center (OEHRC) IMERI (FK) UI dan Yayasan Pure Earth Indonesia, melibatkan sejumlah peneliti dan sivitas akademika UI, seperti dr. Marinda Asiah Nuril Haya M Med Sci Ph D, dr. M. Ilyas Sp Ok Subsp ToksiKO (K), dr. Ade Mutiara MKK Sp Ok, dr. Ari Prayogo Sp A, dr. Dewi Yunia F Sp Ok, dan peneliti dari Yayasan Pure Earth Indonesia, Nickolaus Hariojati.
Prof. Badriul menjelaskan bahwa penelitian mengenai pajanan timbal ini sangat penting karena timbal merupakan neurotoksin berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti cacat lahir, kerusakan otak, masalah kardiovaskular, dan penyakit ginjal.
Timbal juga dapat menyebabkan stres oksidatif jika terpapar dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, tantangan ke depannya adalah merancang strategi preventif dan promotif dalam ilmu kedokteran komunitas untuk mengatasi dan mengurangi pajanan timbal.
Baca juga : Mulai September, Bus Tayo Kota Tangerang Hanya Terima Pembayaran Non-Tunai
Rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa Kadar Timbal Darah (KTD) 5 µg/dL merupakan penanda sumber pajanan lingkungan yang harus diwaspadai. Disarankan agar KTD tidak melebihi angka tersebut. Batas KTD 45 µg/dL digunakan sebagai pertimbangan pemberian terapi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 90 persen anak-anak di lima desa di Pulau Jawa memiliki KTD melebihi batas rekomendasi WHO. Dari jumlah tersebut, 19 anak (3,4 persen) membutuhkan terapi.





 Bagikan
Bagikan